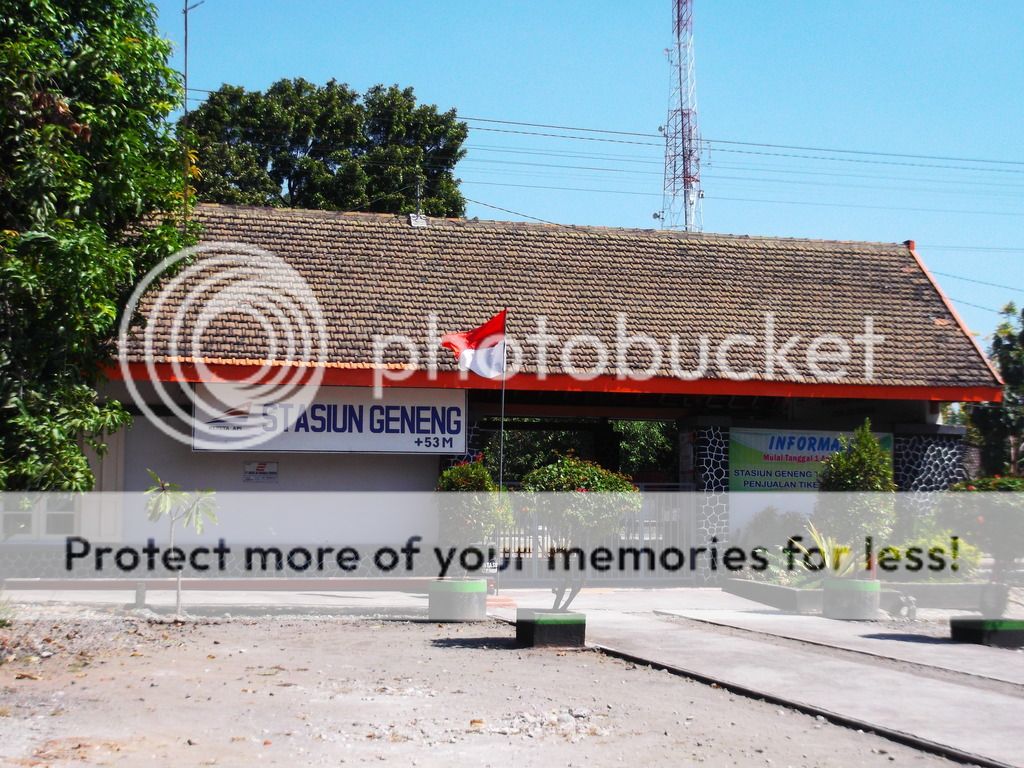Pernahkan
Anda naik bus ekonomi dari Surabaya menuju Solo? Rutenya tidak akan lewat
Karangjati, melainkan lewat Maospati. Ketika perjalanan bus sudah melewati
Maospati menuju Ngawi, Anda bisa menyaksikan pabrik gula peninggalan kolonial
Belanda.
Tepat
wilayah perbatasan antara Magetan dan Ngawi, Anda akan menyaksikan perempatan
kecil yang di sudut barat laut terdapat pajangan lokomotif lori. Di situlah,
Anda akan bisa membaca papan nama penunjuk arah Pabrik Gula (PG) Soedhono ke
arah barat dari situ. Pabrik gula ini terletak di Jalan PG Soedhono, Desa
Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pabrik
gula ini berada di sebelah utara
Stasiun Kereta Api Geneng. Pabrik gula ini
berbatasan dengan Desa Tempuran di sebelah utara, dengan Desa Tambakromo di sebelah
selatan, dengan Desa Sambirobyong di sebelah timur, dan dengan Desa Satrean di
sebelah barat.
Berdasarkan
catatan dari Dorrepal & Co. di
Semarang, selaku kantor asuransi penjamin PG Soedhono, diterangkan bahwa pabrik
gula ini didirikan pada 1 Maret 1888 oleh perusahaan Verenigde Vorsendsche Cultuur Maatschappij yang berkantor pusat di
Semarang.
Pada
awal berdiri, pengelolaan pabrik gula ini masih mengekor sebuah perusahaan
Belanda yang memiliki pabrik gula Kali Bagor di Banyumas (Jawa Tengah). Hanya
terkadang kalau pas menemui masalah yang sedikit agak pelik dalam
pengelolaannya, permasalahannya akan di bawa ke kantor induknya yang berada di
Semarang. Namun, seiring perkembangannya akhirnya pabrik gula mulai melakukan
produksi gula sendiri pada tahun 1924 dan sekaligus membentuk perusahaan
sendiri yang diberi nama
Suikerfabriek
Soedhono van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden bij Ngawi, atau yang
kemudian dikenal dengan PG Soedhono saja.
Pada
waktu Jepang menduduki Hindia Belanda, PG Soedhono ini sempat diambil alih oleh
pasukan Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, semua aset pabrik gula ini
direbut oleh pejuang Indonesia dari cengkeraman pasukan Jepang, dan kemudian
difungsikan kembali sebagai PG Soedono, yang mengolah tebu menjadi gula pasir.
Ketika
Belanda berusaha kembali untuk menjajah Indonesia lagi pada tahun 1949, pabrik
gula ini menjadi rebutan antara pasukan Netherlands
Indies Civil Administration (NICA)
dengan para pejuang Indonesia. Merasa kalah dalam persenjataan, pejuang
Indonesia akhirnya membumihanguskan pabrik gula tersebut agar tidak digunakan
oleh Belanda lagi.
Pada
1951, pabrik gula ini dibangun kembali dan kemudian mulai beroperasi untuk
memproduksi gula lagi yang dipimpin oleh Keyman. Selang tiga tahun, Keyman
digantikan oleh Leyssius. Setelah terjadi perlawanan dari pejuang Indonesia
secara gerilya dan terus menerus, akhirnya memaksa Belanda untuk hengkang dari
Indonesia. Aset prabik gula ini akhirnya dinasionalisasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia.
Pada
10 Desember 1957 dilakukan beberapa perombakan kepengurusan. Direksi sebagai
pimpinan tertinggi Perusahaan Negara (PN) yang berpusat di Jakarta melakukan
perubahan struktur organisasi perkebunan dari sentralisasi menjadi
desentralisasi dan status PG Soedhono menjadi Perusahaan Perkebunan Negara
(PPN). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/1962 dan Nomor
2/1962 tentang Perusahaan Negara (PN) maka PG Soedhono berubah dari PPN menjadi
Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Pada perubahan ini kepemimpinan PG Soedhono
dipegang oleh Doeri Djogowirono.
Terus
secara berturut-turut terjadi pergantian kepemimpinan pabrik gula ini. Pada
1969 pimpinan pabrik gula ini dipegang oleh R. Soenjoto Reksodimuljo, lalu pada
1973 Pamujo, BSc menjadi Direktur PG Soedhono, dan kemudian pada 1977 R.
Pangesoe dipercaya sebagai Kepala PG Soedhono.
Pada
2 Mei 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1972 (Lembaran Negara RI Nomor 7 Tahun 1972) yang menetapkan pengalihan bentuk
PNP XX menjadi Persero, sehingga terjadi perubahan status dari PN menjadi
Persero PTP XX (Perseroan Terrbatas Perkebunan). Berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7749-HT-01-01 Tahun 1983,
telah disahkan berdirinya PTP XX menjadi badan hukum untuk waktu 75 tahun
terhitung sejak tanggal 3 Desember 1983. Pada saat perubahan ini, kepemimpinan
pabrik gula dipegang oleh R. Soebono yang menggantikan R. Soekartiko.
Dalam
Surat Edaran Nomor XX-SURED/96.001, dengan berdasar pada PP Nomor 16/1996
tanggal 14 Februari 1996 maka PTP XX dan PTP XXIV-XXV (Persero) telah
dibubarkan dan tanggal 11 Maret 1996 dibentuk perusahaan baru dengan nama PTP
Nusantara XI (Persero) dengan alamat di Jalan Merak 1 Surabaya.
PG
Soedhono memiliki luas tanah dan bangunan pabrik sekitar 5.000 m²
yang terdiri dari luas bangunan industri dan fasilitas lain sebesar 3.500 m²
dan luas tanah yang tidak tertutup sebesar 1.500 m². Dari luas tersebut, PG
Soedhono masih bisa mengoperasikan pabriknya hingga sekarang bahkan bisa
meningkat. Selain menghasilkan gula pasir sebagai hasil utama, juga
menghasilkan hasil sampingan berupa tetes tebu, ampas tebu, blotong, dan abu ketel. Tetes tebu
dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan Monosodium
glutamat (MSG) dan dalam pengolahan tetes tebu ini PG Soedhono bekerja sama
dengan berapa pabrik pembuat MSG yaitu Cil Cedang, Ajinomoto, dan Sasa. Ampas
tebu diolah menjadi bahan bakar mesin yang digunakan untuk proses produksi gula
pasir. Blotong dan abu ketel
dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan pupuk kompos yang dikelola oleh
koperasi karyawan. *** [040715]
Kepustakaan:
Nita Dwi Kartika Sari, 2012. Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Bebu dalam Pembuatan Gula
Pasir di Pabrik Gula Soedhono Kabupaten Ngawi, dalam Skripsi di FU UNS
http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen8/firmadet83995.shtml
http://www.ptpn-11.com/pg-soedhono.html