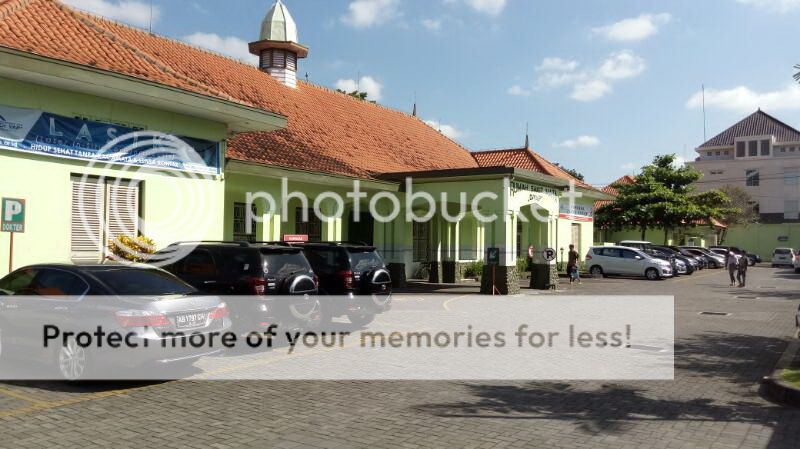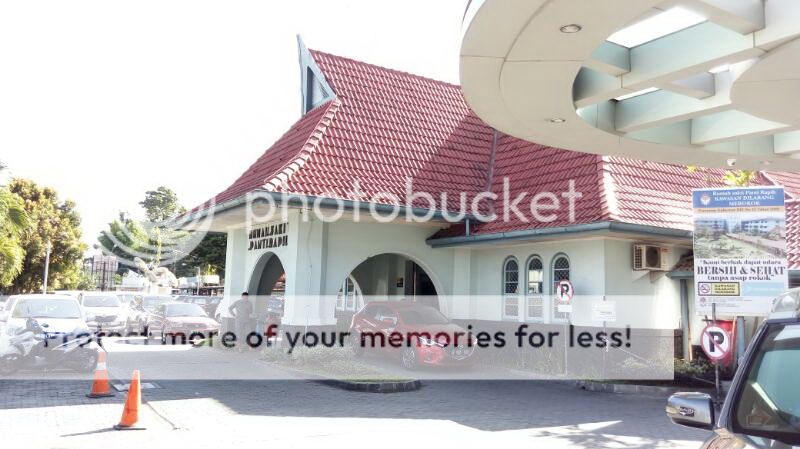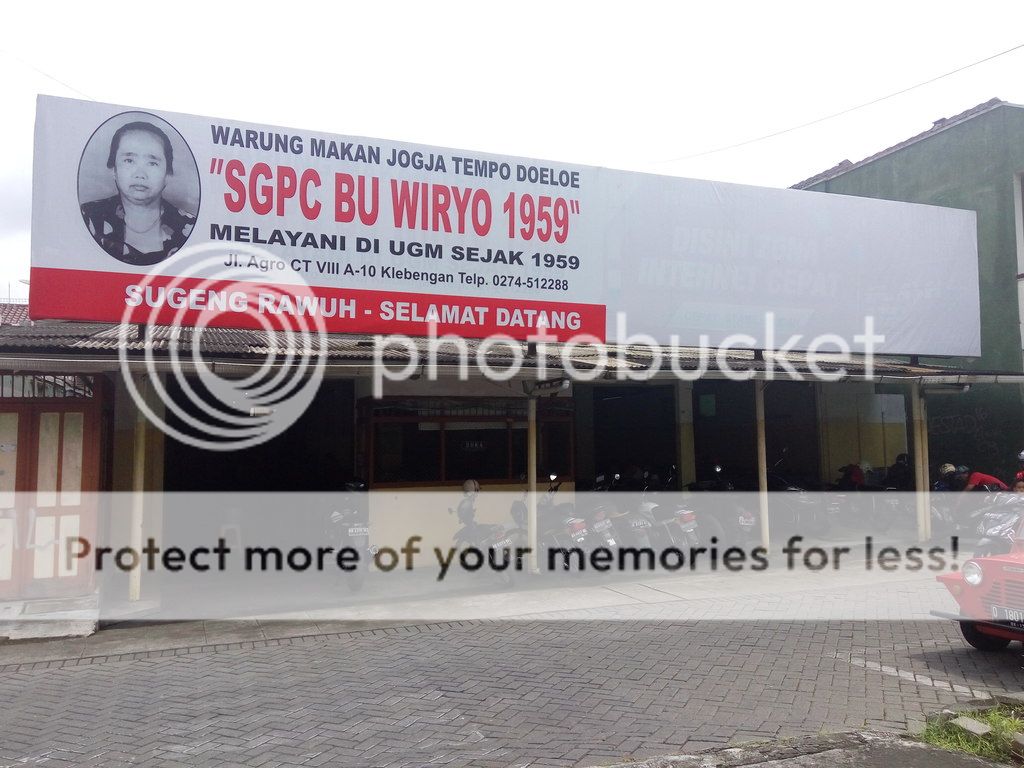-

Istana Ali Marhum Kantor
Kampung Ladi,Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat)
-

Gudang Mesiu Pulau Penyengat
Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]
-

Benteng Bukit Kursi
Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]
-

Kompleks Makam Raja Abdurrahman
Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]
-

Mesjid Raya Sultan Riau
Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]
Tampilkan postingan dengan label Jogja Heritage. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jogja Heritage. Tampilkan semua postingan
Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran
Budiarto Eko KusumoJumat, Agustus 18, 2017Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran, Jogja Heritage, kekunaan, The Church of Sacred Heart in Pugeran
Tidak ada komentar

Pugeran
merupakan sebuah kampung yang berada di bagian selatan Kota Yogyakarta.
Dipilihnya Pugeran sebagai lokasi untuk mendirikan gereja, karena pada waktu
itu di Yogyakarta bagian selatan baru ada satu gereja Katolik, yaitu gereja
yang berada di Ganjuran.
Selain
untuk menampung jemaat Katolik di Yogyakarta bagian selatan dan Bantul bagian
utara, juga untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah umat Katolik di Gereja
Frasiscus Xaverius Kidul Loji dan Gereja Santo Antonius Bintaran. Hal ini yang
menyebabkan muncul ide untuk mendirikan sebuah gereja yang bernama Gereja
Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran, atau biasa disebut dengan Gereja Pugeran. Gereja
ini terletak di Jalan Suryaden No. 63 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogayakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi
gereja ini berada di sebelah timur laut Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Yogyakarta ± 50 m.
Dengan diprakasai oleh Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ, yang didukung oleh para bangsawan Jawa seperti Pangeran Suryodiningrat, Pangeran Tedjokusumo, Pangeran Brotodiningrat, dan Pangeran Puger, gereja itu mulai dibangun pada 5 November 1933 dengan menggunakan hasil rancangan dari seorang arsitek Belanda, Johannes Theodorus van Oijen. Sebelumnya, Van Oijen sudah mendesain Gereja Katolik SantoAntonius Bintaran.
Lahan
tempat pendirian gereja ini merupakan tanah milik beberapa penduduk yang dibeli
oleh Yayasan Papa Miskin, sebuah yayasan Misi di Yogyakarta, yang diatasnamakan
Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ. Lahan tersebut berada di lokasi yang sekarang
menjadi tempat berdirinya gereja ini, yaitu sebuah jalan yang berada antara
pojok Beteng Kulon dan Bantul, yang dikenal dengan nama Pugeran.
Gereja ini kemudian diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Pastor A. Van Klanken SJ, dengan diakon Pastor Rektor Xaverius Muntilan dan subdiakon Pastor A. Sukiman Prawirapratama SJ, bersamaan dengan peringatan 75 tahun Misi Yesuit di Hindia Belanda, dan kemudian esok harinya dilakukan pembaptisan pertama Fransiscus Xaverius Suyatna dari Padokan. Pastor pertama yang ditunjuk untuk berkarya di Gereja Pugeran adalah Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ.
Berdasarkan
catatan tahun 1936, jumlah umat Katolik yang ada di Gereja Pugeran ini adalah
1.010 orang. Sebagian besar umat tersebut terdiri dari umat pribumi Jawa, yang
umumnya berasal dari daerah sekitar Pabrik Gula Padokan, dan sekitar gereja
tersebut.
Dilihat dari arsitekturnya, gereja ini memiliki fasad yang khas dibandingkan dengan gereja-gereja lain pada umumnya. Pada gereja ini terjadi ‘perkawinan’ antara arsitektur tradisonal Jawa dengan arsitektur Barat. Ciri tradisionalnya bisa dilihat dari atapnya yang berbentuk tajug yang lazim digunakan pada bangunan ibadah tradisional Jawa yang dipengaruhi oleh agama Islam. Namun pada ujung atap terdapat sebuah salib untuk menandakan bahwa bangunan itu adalah bangunan gereja. Sedangkan, ciri dari Barat ditandai dengan dinding-dinding gerejanya. Badan bangunan bagian depan menggunakan langgam Neo-Gothic yang menggunakan moulding pada permukaan dindingnya, dan di atas pintu utama gereja tertulis Ad Maiorem Dei Gloriam, yang artinya “Demi kemulian Tuhan yang lebih besar”.
Gereja Pugeran ini merupakan salah satu gereja yang mampu bertahan menghadapi gejolak sosial dan politik, karena Paroki Pugeran mampu menjadi bagian dari lokalitas masyarakat di sekitarnya dengan berperan langsung sebagai bagian dari media perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pada
masa Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda melakukan serangan terhadap
Kota Yogyakarta. Pada saat serangan tersebut, banyak orang mengungsi menuju ke
arah selatan dari Kota Yogyakarta. Halaman Gereja Pugeran penuh dengan
pengungsi. Pastor dan para pembantunya berusaha untuk melindungi dan mengayomi
para pengungsi yang mengungsi di halaman Gereja Pugeran. Mereka mengusahakan
obat-obatan dan makanan bagi para pengungsi serta merawat yang terluka dan
sakit. Sementara, mayat yang bergelimpangan akibat dari perang tersebut, juga
dikuburkan dengan layak oleh pastor dan para pembantunya.
Peristiwa
heroik itu diabadikan dalam sebuah prasasti yang dibangun di depan gereja, dan
tepatnya berada di belakang patung Hati Kudus Yesus. Prasasti tersebut
berbunyi: “Di bawah naungan Hati Kudus
Juru Selamat Kristus para pastor beserta umat paroki Pugeran dengan penuh bakti
serta syukur memperingati hari ulang tahun ke-50 Gereja Hati Kudus tercinta
ini, khususnya dengan kenang-kenangan bahagia bahwa pada hari-hari yang paling
gelap penuh derita 19 Desember 1948 - 19 Juni 1949 selama Perang Kemerdekaan
Republik Indonesia tempat ini telah menjadi pengungsian dan perlindungan bagi
penduduk tak bersalah di sekitar gereja Pugeran dan merupakan tempat penghubung
rahasia pula antara para pejuang gerilyawan Perang Kemerdekaan Republik
Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta”. *** [210717]
Kepustakaan:
http://library.fis.uny.ac.id/elibfis/index.php?p=show_detail&id=998&keywords=
https://www.academia.edu/2348128/Tinjauan_Inkulturasi_Agama_Katolik_dengan_Budaya_Jawa_pada_Bangunan_Gereja_Katolik_di_Masa_Kolonial_Belanda_Studi_Kasus_Gereja_Hati_Kudus_Yesus_Pugeran_
Gereja Katolik Santo Yusup Bintaran
Budiarto Eko KusumoRabu, Agustus 16, 2017Benda Cagar Budaya di Yogyakarta, Gereja Bintaran, Jogja Heritage, kekunaan, Santo Yosep Church in Yogyakarta, Sejarah Gereja Bintaran
Tidak ada komentar

Kawasan
Bintaran merupakan salah satu kawasan permukiman yang dikembangkan oleh
Pemerintah Hnidia Belanda di Yogyakarta. Pengembangan kawasan ini lantaran
permukiman orang-orang Belanda maupun Eropa yang lama di kawasan Kidul Loji atau
Secodiningratan sudah padat. Kawasan Kidul Loji sendiri berada di sebelah
selatan Benteng Vredeburg, yang berjarak satu kilometer dengan kawasan
Bintaran.
Dalam
pengembangan kawasan Bintaran tersebut, juga didirikan fasilitas keagamaan
berupa gereja Katolik yang bernama Gereja Katolik Santo Yusup, atau yang
dikenal juga dengan Gereja Bintaran. Gereja ini terletak di Jalan Bintaran
Kidul No. 5, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi gereja ini berada di depan Bintaran
Mart, atau H Royal Residence Bintaran.
Gagasan mendirikan gereja di Bintaran ini berawal dari keprihatinan akan keterbatasan ruang gereja yang ada di Gereja Santo Frasiskus Xaverius Kidul Loji. Pada waktu itu, Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kidul Loji masih didominasi oleh jemaat yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Orang-orang kulit putih menempati bangunan utama gereja, sedangkan jemaat orang-orang pribumi Katolik memilih menempati gudahng sisi timur gereja.
Seiring
perkembangan waktu, gudang tersebut tak mampu lagi untuk menampung jemaat
pribumi Katoilk. Situasi dan kondisi yang demikian menjadi perhatian Pastor
Henri van Driessche SJ, untuk membangun gereja yang khusus untuk jemaat
orang-orang pribumi Katolik tersebut.
Setelah
penggalangan dana terkumpul, maka dibuatlah desain bangunan gereja yang
dipercayakan kepada Ir. Johannes Theodorus van Oijen. Van Oijen adalah seorang
arsitek berkebangsaan Belanda yang telah banyak berkiprah di kota-kota yang ada
di Hindia Belanda, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ia kelahiran Den
Haag pada 3 Oktober 1896, dan meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung pada 11
Juli 1944.
Pembangunan gereja dimulai pada tahun 1933, dan kontraktor pelaksananya dilakukan oleh sebuah perusahaan bangunan milik Belanda bernama Naamloze Vennootschap (NV) “Hollandsche Beton Maatschappij”. Luas bangunan gereja adalah 720 m² yang berdiri di atas lahan seluas 5024 m². Tinggi bangunan gereja 13 m, lebar 20 m dan panjang 36 m.
Secara
visual bangunan Gereja Bintaran memiliki keunikan bila dibandingkan dengan
gereja-gereja lainnya yang ada di Yogyakarta. Gereja ini mempunyai atap plat
beton lengkung tinggi yang diapit oleh atap datar. Langgam arsitektur gereja
seperti itu hanya ada dua, yang satunya ada di Belanda yang menjadi induk dari
gereja ini.
Gedung
gereja ini diresmikan pada hari Minggu, 8 April 1934 bersamaan dengan misa
ekaristi untuk pertama kalinya yangdihadiri sekitar 1800 jemaat Katolik
pribumi. Peresmian gereja dilakukan oleh Mgr. A. Th. Van Hoof SJ, Vikaris
Apolistik didampingi oleh Pastor Van Kalken SJ, Kepala Misi Jesuit di Jawa dan
Pastor G. Riestra SJ, Pastor Kepala di Yogyakarta. Selain itu, juga dihadiri
oleh dua orang wakil masyarakat Katolik pribumi, Raden B. Djajaendra dan Raden
Mas L. Jama. Keduanya bekas murid sekolah guru Muntilan yang saat itu bekerja
di sekolah Bruderan Yogyakarta.
Setelah
itu, Pastor pertama yang berkarya di Bintaran adalah Pastor A.A.C.M. de Kuyper
SJ dibantu oleh Pastor A. Soegijopranoto SJ. Mereka berdua sudah dipercaya
memegang Paroki Bintaran sejak 12 Oktober 1933, satu tahun sebelum gereja
diresmikan penggunaannya.
Menilik
data antara Juli 1935 sampai Juni 1936 diketahui bahwa, jumlah jemaat Paroki
Bintaran berjumlah 4.695 orang. Dari jumlah itu, hanya ada 26 jemaat orang
Eropa. Selaras dengan ide awal pendirian gereja ini, perbandingan ini telah mengokohkan
bahwa Gereja Bintaran memang merupakan Gereja Katolik Jawa pertama di Yogyakarta.
Anton
Haryono dalam bukunya, Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogykarta 1914-1940 (Kanisius, 2009) menjelaskan bahwa, daerah Yogyakarta merupakan
tanah Misi paling subur di Jawa, yang tidak hanya tercermin dari pertumbuhan
umat, tetapi juga dari kesuburan panggilan imamat dan hidup membiara. Dari
daerah inilah untuk pertama kalinya di Indonesia muncul imam, biarawan, dan
biarawati pribumi. Bahkan, kardinal pertama juga berasal dari daerah Yogyakarta.
Di
sisi lain, gereja ini juga mempunyai peran dalam proses perjuangan kemerdekaan.
Pada saat Ibu Kota Pemerintahan RI dipindahkan ke Yogyakarta, Gereja Bintaran
menjadi tempat persembunyian keluarga Bung Karno dan Hatta yang kala itu
dibuang ke bukit tinggi. Selain itu, gereja ini juga menjadi tempat rintisan
sekolah pribumi Kolese Debrito, dan sering kali digunakan sebagai tempat
pertemuan kelompok gereja Katolik, salah satunya adalah Kongres Umat Katolik
Seluruh Indonesia (KUKSI) yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 17
Desember 1949 yang menghasilkan Partai Katolik Indonesia.
Kini,
Gereja Bintaran menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh negara berdasarkan
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.25/PW.007/MKP/2007 tentang
Penetapan Situs Dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi Di
Wilayah Propinsi DIY Sebagai Benda Cagar Budaya Atau Kawasan Cagar Budaya. *** [210717]
Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Kepustakaan:
Haryono, Anton. (2009). Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di
Yogykarta 1914-1940. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
http://journal.unpar.ac.id/index.php/rekayasa/article/viewFile/1355/1312
http://loncengbintaran.blogspot.co.id/2007/12/sejarah-gereja-santo-yusup-bintaran.html
http://lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id/mengunjungi-gereja-jawa-pertama-di-yogyakarta/
https://www.academia.edu/7666653/Rekam_Jejak_Arsitektur_Indis_di_Bintaran
Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru
Budiarto Eko KusumoSenin, Agustus 14, 2017Cagar Budaya di Jogja, Jogja Heritage, kekunaan, Kotabaru, Sejarah Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru, the Catholic Church of Santo Antonius Kotabaru
Tidak ada komentar

Kotabaru
termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Semula Kotabaru ini
dikenal dengan Nieuwe Wijk, yaitu
permukiman orang-orang Belanda maupun Eropa yang tinggal di Yogyakarta.
Sebagaimana permukiman orang-orang Belanda pada umumnya, permukiman tersebut
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, seperti fasilitas olahraga,
kesehatan, dan keagamaan.
Salah
satu fasilitas keagamaan yang ditemukan di kawasan itu adalah Gereja Katolik
Santo Antonius, yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali No. 1 Kelurahan Kotabaru,
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lokasi gereja ini hoek pertemuan
antara Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan I Dewa Nyoman Oka.
Keberadaan
Gereja Katolik Santo Antonius ini tidak terlepas dari peran Pastor Fransiscus
Xaverius Strater SJ. Ia adalah seorang misionaris Jesuit yang tiba di
Yogyakarta pada tahun 1918. Kedatangannya adalah untuk membantu pengembangan
kegiatan Misi di daerah Yogyakarta yang telah dirintis oleh Pastor Henri van
Driessche.
Semula tugas utamanya adalah karya pastoral bagi orang-orang Katolik Belanda (Eropa), namun kemudian ia tertarik untuk terlibat dalam Misi di antara orang-orang pribumi Jawa. Mengawali karya misinya tersebut, Pastor Fransiscus Xaverius Strater, SJ mendirikan Kolese Santo Ignatius (Kolsani) pada 18 Agustus 1922, dan Seminari Tinggi (Novisiat Kolsani) pada tahun 1924, yang gedungnya sekarang ini digunakan oleh Puskat/IPPAK dan Pusat Musik Liturgi (PML). Dari Kolsani inilah benih-benih kekatolikan ditabur, dan banyak masyarakat yang mengikuti ajaran Katolik.
Di
lingkungan Kolsani itu juga dibangun sebuah kapel untuk tempat kebaktian. Kapel
Kolsani ini mula-mula digunakan untuk orang-orang Kolsani, namun kemudian terbuka
untuk umum. Seiring perjalanan waktu, kapel kian hari kian terlihat sempit
karena jumlah umat bertambah banyak. Hal ini yang menyebabkan Pastor Fransiscus
Xaverius Strater SJ memandang perlu didirikan sebuat tempat peribadatan bagi
umat Katolik yang lebih besar.
Tempat
ibadat, atau gedung gereja, merupakan salah satu sarana penting untuk memenuhi
kebutuhan umat dalam menjalankan upacara-upacara keagamaan. Keberadaannya yang
permanen dan mudah dijangkau memungkinkan umat untuk mengikuti perayaan Misa dan
kegiatan-kegiatan rohani lainnya dengan lebih teratur. Selain itu, gereja
sebagai tempat perjumpaan rutin, secara sosial dapat memperteguh eksistensi
komunitas kecil umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Menilik kebutuhan
fungsionalnya, lembaga Misi kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk dapat
membangun gedung-gedung gereja.
Provinsial
Serikat Jesus Hindia Belanda saat itu, yaitu Pastor J. Hoeberechts, berusaha
menggalang dana untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar dan
representatif guna menampung umat Katolik baru yang semakin bertambah.
Akhirnya, Pastor J. Hoeberechts mendapat bantuan atau donatur dari seorang
wanita di Belanda untuk membangun gereja di Kotabaru, tapi dengan syarat nama
gereja yang disandangnya hendaknya diberi nama Santo Antonius van Padua.
Setelah itu, pembangunan gereja pun mulai direalisasikan. Pastor J. Hoeberechts menyerahkan desain bangunan kepada Cuypers melalui biro arsitek ternama dari Batavia, NV Architecten-Ingenieursbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam, atau biasa disingkat menjadi Biro Arsitek Fermont-Cuypers, yang memang sudah menghasilkan lusinan karya di Hindia Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan gereja tersebut, desain awal Cuyper mengalami perubahan. Seharusnya lebih luas, besar, dan megah, tetapi karena keterbatasan lahan dan biaya pada waktu itu. Menara depan yang seharusnya memakai kubah diganti menjadi mengerucut ke atas. Begitu pula, bangunan di sisi kiri dan kanan dari gereja, dikurangi lebarnya. Akhirnya terwujud bangunan gereja seperti sekarang ini.
Setelah
selesai, Gereja Santo Antonius Kotabaru diresmikan pada 26 September 1926
dengan pemberkatan oleh Mgr. A. van Velsen SJ, Uskup Batavia yang juga
membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain unutk kebaktian, gereja tersebut
juga difungsikan sebagai tempat para calon imam muda berlatih. Karena kala itu,
gereja tersebut masih merupakan milik Kolsani. Rektor Novisiat Kolsani, yaitu
Pastor Fransiscus Xaverius Strater SJ, sekaligus menjabat sebagai Pastor Kepala
Paroki Santo Andonius Kotabaru. Dulunya, Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru
merupakan stasi dari Paroki Kidul Loji, namun kemudian pada 1 Januari 1934
menjadi paroki yang berdiri sendiri.
Pada
masa pendudukan Jepang tahun 1942, bangunan gereja ini dikuasai oleh tentara
Jepang, dan digunakan sebagai gudang. Sementara itu, bangunan Kolsani menjadi
tempat penampungan interniran bagi suster-suster dan wanita-wanita Belanda,
sedangkan Seminari Tinggi yang berada di sebelah barat gereja difungsikan
sebagai kantor bagi tentara Jepang. Keadaan yang seperti ini, menyebabkan Pastor
Fransiscus Xaverius Strater SJ meninggal sebagai internir, dan tempat ibadat
umat Katolik dipindahkan ke bangunan rumah kuno berbentuk Joglo yang berada di
daerah Kemetiran.
Setelah
Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, dan Indonesia merdeka,
Kolsani dan Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru difungsikan kembali menjadi
tempat pendidikan dan gereja seperti semula. Aktifnya kembali gereja ini,
menyebabkan rumah Joglo Kemetiran menjadi paroki yang berdiri sendiri.
Pada
tahun 1967 Kolsani menyerahkan pengelolaan gereja kepada paroki untuk
mendewasakan Paroki Santo Antonius Kotabaru, namun pemisahan sepenuhnya baru
terjadi pada tahun 1975. Paroki Santo Antonius Kotabaru selanjutnya tumbuh
menjadi suatu paroki yang berdikari dalam segala bidang hingga saat ini. *** [210717]
Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Keputakaan:
Heuken SJ, Adolf. (2003). Gereja-gereja tua di Jakarta. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka
Haryono, Anton. (2013). Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogyakarta 1914-1940.
Yogyakarta: Penerbit Kanisius
http://travelheritage.id/artikel/detail/19-gereja-katolik-santo-antonius-kotabaru-yogyakarta
Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru
Budiarto Eko KusumoSabtu, Agustus 12, 2017Cagar Budaya, Jejak Kolonial, Jiwasraya at Kotabaru, Jogja Heritage, kekunaan, NILLMIJ, Sejarah Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru
1 komentar

Kawasan
Kotabaru, yang dulunya disebut Nieuwe
Wijk, merupakan sebuah wilayah khusus yang didirikan untuk permukiman orang
Belanda maupun Eropa lainnya. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1920-an.
Pembangunan kawasan ini merupakan konsekuensi dari kian berkembangnya jumlah
orang Belanda maupun Eropa yang ada di Yogyakarta. Perkembangan tesebut tidak
terlepas dengan adanya industri gula dan perkebunan-perkebunan lainnya.
Desain
kawasannya sangat rapi dengan pemanfaatan ruang yang teratur. Ada bangunan
rumah, taman. Fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan maupun fasilitas
kesehatan. Bangunan-bangunan dirancang dengan gaya arsitektur Eropa yang
disesuaikan dengan iklim alam setempat. Salah satu bangunan peninggalan kolonial
Belanda yang masih bisa ditemui sampai sekarang adalah Kantor Asuransi
Jiwasraya. Kantor ini terletak di Jalan Faridan Muridan Noto No. 9 Kelurahan
Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Lokasi kantor ini berada di sebelah timur SDN Ungaran, atau berada
di hoek Jalan Faridan Muridan Noto
dan Jalan Ungaran.
Gedung Kantor Asuransi Jiwasraya itu semula merupakan rumah untuk kediaman salah satu pegawai Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ). NILLMIJ merupakan sebuah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan di Hindia Belanda pada 31 Desember 1859.
Dalam
perjalanan yang cukup panjang, NILLMIJ ini pernah mengalami pelbagai perubahan
nama. Dimulai ketika perusahaan asuransi ini dinasionalisasi pada tahun 1960,
hingga sekarang menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 1998. Oleh
karena itu, gedung bekas kediaman pegawai NILLMIJ yang terdapat di Kotabaru pun
lantas ikut menjadi aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan saat ini
dijadikan sebagai Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru.
Pada
masa pendudukan Jepang, Kotabaru dan hunian Belanda lain di Yogyakarta diambil
alih oleh Jepang, antara lain untuk kepentingan perkantoran, perumahan, tangsi,
dan gudang. Khusus untuk bangunan milik NILLMIJ ini dijadikan untuk tempat
tinggal Butaico Mayor Otsuka, perwira tinggi angkatan bersejata Jepang.
Pada 6 Oktober 1945, Mohammad Saleh (dari KNID), R.P. Sudarsono (Polisi Istimewa), Sunyoto, Bardosono (dari BKR) mengadakan pembicaraan dengan pimpinan tentara Jepang yaitu Mayor Otsuka, Kenpeito Sasaki, Kapten Ito dan Kiabuco di bangunan NILLMIJ itu. Dalam pertemuan itu, Jepang diminta agar mau menyerahkan senjatanya dan menyerahkan kewajiban menjaga ketentraman dan keamanan dalam negeri. Akan tetapi, Jepang tetap bersikeras tidak mau menyerahkan senjata, dengan demikian tidak ada jalan lain selain melalui jalan kekerasan atau pertempuran.
Akhirnya,
para pejuang bersama pemuda di Yogyakarta berusaha mengepung kediaman Mayor
Otsuka yang dianggap sebagai pusat markas pasukan Jepang dari berbagai arah.
Karena mengetahui markasnya terkepung, Jepang pun memberi perlawanan dengan
memuntahkan peluru mitraliyurnya terhadap pasukan dan pemuda Indonesia dari
tempat-tempat persembunyiannya. Pasukan rakayat yang telah disiagakan sejak
sore hingga malam hari tanggal 6 Oktober 1945, terus mendesak masuk ke dalam
markas Jepang, sehingga terjadi peperangan satu lawan satu dari jarak dekat
yang berlangsung sampai menjelang siang hari. Beberapa saat kemudian mereka
dapat bergerak mendekati kubu pertahanan Jepang.
Pada
saat pertempuran tengah berlangsung, Butaico yang bermarkas di Pingit datang ke
Kotabaru. Dengan senang hati Butaico Pingit menyerahkan senjatanya dengan
syarat anak buahnya tidak diganggu. Pimpinan TKR lalu meminta agar Butaico
Pingit menasehati Mayor Otsuka untuk bersedia mengikuti jejaknya menyerahkan
senjata mereka kepada Indonesia. Namun Otsuka belum mau menyerahkan
senjata-senjata tersebut. Karena itu pertempuran berjalan semakin memanas. Dalam
suatu kesempatan, Mohammad Saleh dan R.P. Sudarsono berhasil masuk ke dalam
tangsi Jepang, menemui Mayor Otsuka. Mereka kembali mendesak Butaico Kotabaru
tersebut untuk menyerah, agar tidak lagi menimbulkan korban di antara kedua
belah pihak. Pada akhirnya karena keadaan terjepit, Butaico Mayor Otsuka memberi
jawaban akan menyerahkan snjatanya, tetapi hanya kepada Yogyakarta Ko (Kepala Daerah Yogyakarta) Sri Paduka Sultan Hamengku
Buwono IX. Setelah pernyataan ini, perlawanan Jepang semakin berkurang dan sekitar
pukul 10.30 tanggal 7 Oktober 1945 dari tengah-tengah pertahanan Jepang
berkibar bendera putih tanda Jepang menyerah. Selanjutnya Butaico Mayor Otsuka
memerintahkan anak buahnya menghentikan pertempuran serta menyerahkan senjata
mereka kepada bangsa Indonesia. ***
[210717]
Foto:
Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Kepustakaan:
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2016/03/30/holland-kecil-di-residentie-yogyakarta/#
http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_246_H/files/res/downloads/download_0049.pdf
Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoJumat, Agustus 11, 2017Bethesda Hospital, Cagar Budaya, Jogja Heritage, kekunaan, Rumah Sakit di Jogja, Sejarah Rumah Sakit Bethesda
Tidak ada komentar

Kawasan
Kotabaru merupakan kawasan permukiman orang-orang Eropa yang dibangun usai
Perang Dunia I, atau pada akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII
(1877-1921). Kawasan ini merupakan kawasan yang benar-benar baru dibangun
terpisah dari Kota Lama Yogyakarta.
Meskipun
permukiman itu dikenal dengan Kotabaru, akan tetapi banyak bangunan lawas yang masih menghiasi di kawasan
tersebut. Salah satu bangunan yang masih memperlihatkan kekunaannya adalah Rumah
Sakit Bethesda. Rumah sakit ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 70
Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondukusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Lokasi rumah sakit ini berada di depan Mall Galeria, atau
sebelah utara Universitas Kristen Duta Wacana ± 400 m.
Sejarah
Rumah Sakit Bethesda tidak dapat dilepaskan dari dinamika zending yang ada di Yogyakarta. Dalam catatan pada Repertorium van Nederlandse zendings- en
missie-archieven 1800-1960 diterangkan bahwa, rumah sakit yang dibangun di
Yogyakarta itu merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan guna
mengembangkan misi gereja, yang pada waktu itu dikenal dengan Gereformeerde Kerken. Gereformeerde Kerken, atau lengkapnya Christelijke Gereformeerde Kerken,
adalah suatu kelompok gereja Kristen Protestan di Belanda, yang dalam bahasa
Inggris disebut Christian Reformed
Churches in the Netherlands.
Ryadi Goenawan dan Darto Harmoko dalam bukunya Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh (1993) menjelaskan bahwa sejak kebangkitan gerakan zending itu, pada tahun 1897 perkembangan agama Kristen di Yogyakarta semakin pesat. Hal ini berkat usaha seorang dokter berkebangsaan Belanda bernama dr. Jan Gerrit Scheurer. Sebelumnya, ia pernah membuka praktek dokter di Gilingan, Solo (1895-1896) bersama istrinya yang bernama Geriitjen van de Riet, dan dibantu oleh Yoram, Sambiyo Reksohusodo dan Kalam Efrayim. Di dalam rumah sewanya itu, kamar makan dirombak menjadi kamar bedah, meja makannya digunakan untuk meja operasi atau bedah. Sebelum memeriksa orang sakit, lebih dahulu dibacakan Alkitab dan berdoa. Tiap hari Minggu diadakan kumpulan untuk merenungkan Firman Tuhan dengan tanya jawab. Dr. Jan Gerrit Scheurer dan pembantu-pembantunya bekerja giat dilandasi sifat kasih sayang.
Ketika
Residen Surakarta, Hora Siccama mengetahui bahwa dr. Jan Gerrit Scheurer juga
memberitakan Injil, izin praktek pun dicabut. Ia pun kemudian pindah ke
Purworejo lagi. Tapi kemudian ia mendapat kepercayaan dari Sinode Middelburg
untuk membangun sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Sebuah yayasan yang disebut
“Rumah Sakit Dr. Scheurer” didirikan dengan dukungan penuh dari tokoh
Gereformeerde terkemuka, seperti Abraham Kuyper dan dr. F.L. Rutgers.
Di kota ini ia bertempat tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Bintaran. Pada 17 Maret 1897 merupakan awal kerjanya saat mendirikan rumah darurat dari bambu di samping rumahnya untuk tempat praktek pengobatan. Bangunan ini selesai pada bulan Juli 1897. Digantungkan sebuah papan bertuliskan, “Gusti Yesus Poenika Djoeroe Wiloedjeng Sedjatos”. Mulailah kerja yang akan dicatat oleh sejarah sebagai gerak perkembangan agama Kristen di daerah Kota Yogyakarta.
Pada
1 Juli 1897 poliklinik sederhana itu dibuka dengan pemuda Yoram sebagai
pegawainya. Tidak ada upacara pembukaan dan tidak ada pesta, yang ada hanya
semangat kerja dan cinta-kasih untuk mereka yang menderita serta memerlukan
perawatan kesehatan. Pada bulan-bulan pertama orang yang datang ke poliklinik
untuk berobat antara 10-15 orang. Hanya dalam waktu satu setengah tahun yang
datang berobat tercatat sebanyak 15.367 orang. Selama itu dr. Jan Gerrit
Scheurer telah berhasil menjalankan operasi dengan narcose sebanyak 12 kali hanya dengat peralatan sederhana dan di atas
meja makan.
Kebutuhan akan ruangan dalam perawatan orang-orang sakit semakin terasakan. Terpaksa direncanakan membangun sebuah rumah sakit dengan kapasitas 150 tempat tidur. Berbagai instansi membantu keinginan dr. Jan Gerrit Scheurer ini, khususnya dari Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebidang tanah di daerah Gondokusuman, seluas 30.000 meter persegi dihadiahkan. Tanah ini sebelumnya merupakan kebun tebu milik Onderneming Muja-Muju, Sultan memberikan ganti kepada perkebunan tebu Muja-Muju untuk menempati daerah lain. Saat itu, tanah yang akan dipakai sebagai bangunan rumah sakit berada di luar dari apa yang disebut Kota Yogyakarta.
Pada
20 Mei 1899 peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dilakukan oleh anak
dr. Jan Gerrit Scheurer. Simbolisme ini melambangkan keinginan sang dokter agar
cita-citanya diteruskan oleh anaknya. Pada 1 Maret 1900 dapat diselesaikan dua zaal untuk merawat penderita pria dan
wanita. Pada 13 Maret 1900 ada 15 pasien yang dirawat di bangunan itu, di
antaranya seorang wedana dari Madiun yang harus dioperasi. Kehadiran wedana ini
ternyata cukup memberikan arti bagi rumah sakit. Masyarakat lebih mengharapkan
berperanannya rumah sakit ini khusunya bagi mereka yang tinggal di Kota
Yogyakarta. Ada kaitan kehadiran seorang pejabat di rumah sakit sebagai pasien
dengan pengharapan dan kepercayaan masyarakat yang semakin besar atas
usaha-usaha di bidang kesehatan masyarakat dari Zending.
Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan perencanaan pembangunan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta bernama Coeverden Andriani. Permintaan sang pendeta yaitu, agar rumah sakit ini diberi nama “Petronella”, sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.
Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan perencanaan pembangunan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta bernama Coeverden Andriani. Permintaan sang pendeta yaitu, agar rumah sakit ini diberi nama “Petronella”, sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.
Perkembangan
rumah sakit yang berawal dari poliklinik di Bintaran kini telah memiliki tiga zaal laki-laki dan dua zaal wanita hanya dalam waktu beberapa
tahun. Nama yang diberikan untuk rumah sakit yakni Zendingshospitaal “Petronella”.
Masyarakat waktu itu mengenalnya sebagai “Dokter Tulung”. Kata ‘tulung’ berasal dari pitulungan (bahasa Jawa) yang bermakna
pertolongan, karena dalam pelayanan terhadap pasien, rumah sakit ini tidak
memandang apa dan siapa pasien itu, namun mengutamakan pertolongan lebih
dahulu.
Direktur
rumah sakit untuk kali pertamanya dipegang oleh dr. Jan Gerrit Schuerer, karena
memang dialah yang merintis rumah sakit ini. Kepemimpinan dr. Jan Geriit
Schuerer berakhir pada tahun 1906, dan digantikan oleh H.S. Pruys. Semula ia
adalah dokter militer dan pembantu dr. Jan Gerrit Scheurer. Semasa kepemimpinan
dr. H.S. Pruys yang menjabat dari tahun 1906 sampai tahun 1918, pendidikan
untuk juru rawat semakin diintensifkan dan untuk pendidikan jenis ini diterbitkan
buku pelajaran dalam bahasa Jawa. Pendidikan di bidang kebidanan mulai
dirintis. Selam bertugas di Rumah Sakit Petronella, dr. H.S. Pruys tidak pernah
mengambil cuti ke Negeri Belanda. Pada tahun 1918 ia harus meninggalkan kerja
yang dicintainya karena menderita sakit. Ditunjuk sebagai pengganti adalah dr.
J. Offringa, yang sejak tahun 1912 telah mendampingi dr. H.S. Pruys.
Kebijakan
dari pimpinan dr. J. Offringa membuahkan semakin banyaknya orang-orang yang
membutuhkan perawatan kesehatannya datang ke Rumah Sakit Petronella. Banyaknya
pasien yang berobat ke Rumah Sakit Petronella menjadikan perlunya penambahan
ruangan atau perluasan rumah sakit ini. Tahun 1920 dr. J. Offringa mengajukan
rencana kepada Gereformeerde Kerken in
Nederland di Amsterdam untuk memperbesar Petronella Ziekenhuis agar dapat menampung 500 pasien. Rencana ini
diterima oleh Gereformeerde Kerken in
Nederland, bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memberikan tanah yang
luas membujur ke barat dan berbatasan dengan Jalan Bedog, serta di bagian
selatannya dengan Militaire Hospitaal.
Tahun 1924 pembangunan dimulai dan selesai pada tahun 1925. Bantuan ini
didapatkan tidak saja dari pemerintah daerah dan pusat tetapi juga dari
pabrik-pabrik gula, onderneming-onderneming
tembakau, perusahaan kereta api de
Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij. Selesainya pembangunan gedung
baru itu tepat juga 25 tahun usia rumah sakit ini sejak peletakan batu pertama
pada 20 Mei 1899.
Setelah
kepempinan dr. J. Offringa (1918-1930), kepemimpinan rumah sakit berturut-turut
dipegang oleh dr. K.P. Groot (1930-1942) dan dr. L.G.J. Samallo (1942-1949).
Ketika masa pendudukan Jepang (1942-1945), rumah sakit ini namanya diganti
dengan Yogyakarta Tjuo Bjoin, dan
kemudian setelah terlepas dari penjajahan Jepang, rumah sakit ini dikenal
sebagai Rumah Sakit Pusat.
Agar
masyarakat umum mengetahui bahwa Rumah Sakit Pusat ini merupakan salah satu
rumah sakit pelayanan kasih (Kristen), maka pada 28 Juni 1950 diganti dengan
nama Rumah Sakit Bethesda yang mempunyai arti kolam penyembuhan.
Sekarang,
Rumah Sakit Bethesda ini merupakan rumah sakit swasta kelas utama tipe B yang
ada di Kota Yogyakarta. Pemiliknya adalah Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
(YAKKUM) yang bermarkas di Solo. Rumah sakit ini dikenal sebagai pusat layanan
kesehatan yang terkemuka di Kota Yogyakarta, karena dikenal memiliki standar
kesehatan yang tinggi dengan sumber daya manusianya yang berkualitas, dan
mengutamakan pelayanan yang cepat terhadap pasien-pasiennya. *** [210717]
Foto:
Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Kepustakaan:
Gunawan, Ryadi & Harnoko, Darto. (1993). Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional
https://colonialhospitals.files.wordpress.com/.../formulier-z_1890_19101.docx
http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/1279604462
https://www.scribd.com/doc/220918518/Laporan-Pkpa-Rs-Bethesda-April-mei-2013
Gedung Manulife Financial Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoSelasa, Mei 23, 2017Cagar Budaya di Jogja, Gedung Manulife Financial Yogyakarta, Jogja Heritage, kekunaan, Manulife Financial Building
Tidak ada komentar

Setelah
sempat singgah sebentar di The Phoenix Hotel, saya melanjutkan perjalanan ke
Stasiun Yogyakarta untuk kembali ke Solo. Sebelum sampai stasiun, saya sempat
melihat sebuah bangunan lawas yang
masih berdiri kokoh namun dinding penuh dengan mural. Bangunan lawas tersebut adalah Gedung Manulife
Financial. Gedung ini terletak di Jalan Margo Utomo No. 20 Kelurahan Gowongan,
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi
gedung ini berada di sebelah utara Hotel Grand Zuri atau selatan PT Pertamina
Sales Area Yogyakarta Pemasaran BBM Retail Region IV.
Gedung
Manulife Financial ini dulunya merupakan tempat menjual aneka peralatan musik
dari sebuah firma yang bernama W. Naessens & Co. (De showroom van Naessens & Co. te Djocja) atau masyarakat Jogja
pada waktu itu mengenalnya sebagai Toko Musik W. Naessens & Co. Firma ini
didirikan oleh J.W.Th. Naessens di Hindia Belanda pada tahun 1891. Dia lahir
pada tahun 1862 di Zaltbommel, dan kemudian memulai karirnya sebagai seorang
pianis. Pada waktu melakukan tur konser di Hindia Belanda, ia tertarik untuk
tinggal di sana dan memutuskan untuk menetap di Surabaya. Talenta bisnisnya
menuntun dia untuk usaha penjualan piano dan alat musik lainnya, baik impor
maupun dengan cara memproduksi piano sendiri di Hindia Belanda dengan
menggunakan kayu jati pilihan.
Pada tahun 1897 firma W. Naessens & Co. membuka cabang di Batavia, kemudian pada tahun 1911 menyusul pembukaan cabang di Semarang dan Medan. Pada tahun 1913 dibuka cabang lagi di Yogyakarta. Jadi, bangunan gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1913 bersamaan dengan pembukaan cabang di Yogyakarta tersebut (Firma W. Naessens & Co. filial Djocja).
Kemudian
gedung ini mengalami pergantian kepemilikannya, dan dalam perjalanannya dikenal
dengan sebutan gedung Manulife Financial, karena gedung ini pernah menjadi
Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Financial yang mana pemegang saham terbesarnya
adalah Manulife Financial Corporation, sebuah perusahaan penyedia layanan
keuangan terdepan yang bermarkas di Kanada.
Setelah
Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Financial pindah ke Jalan HOS Cokroaminoto,
gedung ini kemudian miliki ole PT XL Axiata Tbk. Pindah kepemilikan tersebut
membawa konsekuensi terjadi pergantian nama gedung tersebut, dan menjadi Gedung
Graha XL. Penamaan Gedung Graha XL ini pun akhirnya harus berakhir pada waktu
terjadi eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 10 Maret
2015.
Pada
waktu penetapan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya, kepemilikan atas
gedung ini masih ada di PT XL Axiata Tbk sehingga penetapannya masih atas nama
Gedung Graha XL. Akan tetapi dengan adanya kisruh kepemilikan lahan tersebut,
untuk memudahkan pengelolaan oleh BPCB Yogyakarta, gedung ini dinamai Gedung Manulife
Financial atau atas nama pengguna gedung sebelum PT XL Axiata Tbk.
Gedung
ini ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.25/PW.007/MKP/2007 dengan nomor registrasi nasional
RNCB.20070326.02.000155. *** [010417]
Kepustakaan:
http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/public/objek/detailcb/PO2016041200108/Gedung-Manulife-Financial
http://www.pianola.nl/Pianola_Museum/W._Naessens_%26_Co..html
The Phoenix Hotel Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoSenin, Mei 22, 2017Hotel di Jogja, Jogja Heritage, kekunaan, Sejarah Hotel Phoenix Yogyakarta, The Phoenix Hotel Yogyakarta
Tidak ada komentar

Pelan
tapi pasti, itulah kira-kira perjalanan saya menggunakan kaki dari PSKK UGM
menuju Stasiun Yogyakarta. Pelan di sini bukan berarti lelet atau lamban dalam
berjalan, melainkan dalam jalan kaki tersebut ada unsur sambil menikmati
keindahan bangunan lawas yang
dilewati. Sehingga, tiap kali menemukan bangunan lawas, saya berusaha berhenti untuk melihat, menanyakan kisahnya
dan memotretnya.
Di
antara bangunan lawas yang saya
singgahi adalah The Phoenix Hotel. Hotel ini terletak di Jalan Jenderal
Sudirman No. 9 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi hotel ini berada di sebelah timur
Bank Mandiri Graha Tugu atau Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Menurut
historisnya, hotel ini dulunya merupakan bangunan rumah tempat tinggal Kwik
Djoen Eng yang dibangun pada tahun 1918. Kwik Djoen Eng adalah seorang Tionghoa
yang berusaha membangun usahanya di Hindia Belanda kala itu. Ia bersama
saudaranya (Kwik bersaudara) pertama kali mendirikan usahanya di Solo pada Juli
1894 dengan nama NV Kwik Hoo Tong Handel
Maatschappij, yang bergerak dalam bidang ekspor impor hasil bumi (terutama teh
dan gula). Usahanya ini sempat berkembang pesat hingga mengantarkan Kwik Djoen
Eng menjadi saudagar kaya, dan NV Kwik
Hoo Tong Handel Maatschappij menjadi firma di Hindia Belanda yang mampu
mempunyai jaringan perdagangan yang luas di Asia Tenggara, Asia Timur bahkan
sampai ke Eropa dan Amerika. Sekitar tahun 1920, perusahaan dagang Kwik
bersaudara ini, kantor pusatnya dipindahkan ke Semarang sampai mengalami
kebangkrutan pada tahun 1932 karena resesi ekonomi.
Akibat krisis ekonomi tersebut, banyak properti yang dimiliki oleh Kwik Djoen Eng yang tersebar di sejumlah daerah, harus lepas kepemilikannya. Ada yang disita oleh Javasche Bank, dan ada pula yang dijual sendiri. Termasuk di antaranya adalah rumah tinggalnya yang berada di Yogyakarta tersebut. Rumah bergaya Indis (Indische Landhuis) tersebut dijual kepada Liem Djoen Hwat. Oleh Liem Djoen Hwat, rumah tersebut disewakan kepada orang Belanda yang bernama D.N.E. Franckle. Franckle kemudian mengubah rumah tempat tingal menjadi sebuah hotel yang diberi nama Hotel Splendid.
Pada
tahun 1942 pasukan Jepang berusaha menduduki Yogyakarta. Hotel yang semula
dirintis oleh Franckle tersebut, akhirnya dikuasai oleh pasukan Jepang yang
kemudian berganti nama menjadi Hotel Yamato. Penyematan nama Yamato ini hanya
bertahan hingga hengkangnya Jepang pada tahun 1945, dan hotel tersebut kembali
ke pemiliknya, yaitu Liem Djoen Hwat.
Pada
tahun 1946 sampai dengan 1949 ketika Yogyakarta menjadi ibu kota dari
pemerintahan Indonesia, bangunan bekas Hotel Splendid atau Hotel Yamato
tersebut digunakan sebagai Kantor Konsulat China. Selang dua tahun kemudian,
bangunan bekas Kantor Konsulat kembali digunakan sebagai hotel lagi. Hotel
tersebut bernama Hotel Merdeka. Pergantian nama menjadi Hotel Merdeka ini
bertahan hingga tahun 1987.
Setelah
selesai difungsikan sebagai Hotel Merdeka, bangunan lawas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang pada saat itu
telah berada di tangan cucunya. Lalu, bangunan tersebut direnovasi tanpa
mengubah bentuknya dan pada tahun 1993 kembali difungsikan sebagai hotel, yang
diberi nama Phoenix Heritage Hotel.
Sepuluh
tahun kemudian, jaringan Accor Hotel Group mengambil alih manajemen Phoenix
Heritage Hotel. Perubahan manajemen ini dibarengi dengan melakukan renovasi
besar-besaran pada hotel ini. Setelah selesai renovasi, pada 14 Mei 2004 nama
Phoenix Heritage Hotel resmi berganti nama menjadi Grand Mercure. Perubahan
nama tersebut bertahan sampai dengan 29 Maret 2009, dan pada 30 Maret 2009,
nama Grand Mercure diganti menjadi The Phoenix Hotel Yogyakarta hingga
sekarang.
Kini,
The Poenix Hotel Yogyakarta telah menjelma menjadi hotel bintang lima, dan
berada jantung kota yang strategis letaknya. Namun demikian, hotel ini masih
mempertahankan bangunan awalnya yang menjadi ciri dari keunikan bangunan
tersebut sebagai fasadnya kendati di halaman belakangnya telah ada penambahan
bangunan baru untuk menopang kelengakapan fasilitas hotel tersebut.
Berdasarkan
Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bangunan The Phoenix
Hotel Yogyakarta ini sudah dimasukkan dalam Daftar Entitas Kebudayaan sebagai
cagar budaya dengan kode pengelolaan KB001561. *** [010417]
Kepustakaan:
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2017/03/16/2468/
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index71.php?kode=046013&level=3
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19555/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7E086742B0539D6C4AE379C687E13422?sequence=3
Indraloka Family Homestay Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoMinggu, Mei 14, 2017Homestay di Jogja, Indraloka Family Homestay Yogyakarta, Jogja Heritage, kekunaan, Sejarah Homestay Indraloka
Tidak ada komentar

Kawasan
Jalan Cik Di Tiro tempo doeloe di
mulut orang Belanda dikenal dengan Yap
Boulevard. Boulevard itu berasal dari bahasa Perancis, yang artinya suatu
jalan lebar nan ramai. Biasanya pada boulevard
terdapat median pemisah, dan di kiri maupun kanannya ada tanaman peneduhnya
yang cukup rindang. Jalan Cik Di Tiro dari dulu hingga sekarang masih seperti
dulu, tidak banyak mengalami perubahan lebar jalan. Hanya saja pohon-pohon
peneduhnya sudah mulai hilang seiring kawasan tersebut berubah menjadi kawasan
komersial.
Namun
demikian, jalan tersebut masih mencitrakan sebagai kawasan tempo doeloe yang banyak berdiri bangunan lawasnya. Salah satu bangunan lawas yang masih bisa kita jumpai adalah
Indraloka Family Homestay. Homestay
ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 18 Kelurahan Terban, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi homestay ini berada di pojok pertigaan
ke Sagan atau pertemuan antara Jalan Cik Di Tiro dengan Jalan Kartini.
Menurut
catatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, bangunan
Indraloka Family Homestay ini dulunya merupakan rumah milik orang Belanda yang
bernama Van der Vin, yang dibangun pada tahun 1930.
Ketika tentara Jepang menduduki Yogyakarta, bangunan rumah Van der Vin ini sempat terlantar karena pada waktu pasukan tentara Jepang berusaha memenjarakan orang-orang Belanda maupun orang Eropa lainnya yang berada maupun bermukim di Yogyakarta. Mereka pada umumnya menjadi interniran.
Pada
waktu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, rumah tersebut pernah
menjadi rumah dinas Dr. Prawoto Mangkusasmita, salah seorang anggota parlemen
dari Partai Masyumi. Setelah ibu kota Republik Indonesia balik kembali ke
Jakarta, rumah tersebut berada di bawah kewenangan Jawatan Perumahan
Yogyakarta.
Pada
tahun 1960 rumah tersebut dibeli oleh Moerdiyono Danoesastro, seorang ambtenaar di Yogyakarta. Prof. Dr.
Soebakdi Soemanto, S.U. dalam Diskusi Great Thinker Umar Kayam di Sekolah
Pascasarjana UGM pada 24 Mei 2011 menuturkan bahwa ‘priyayi’ yang dilukiskan
dalam novel ‘Para Priyayi’, bukan priyayi yang berdarah biru tetapi kelas bawah
yang berproses bergerak secara vertikal dan kemudian berada di kalangan elitis.
Pada zaman penjajahan Belanda, mereka disebut ambtenaar. Pada zaman republic awal hingga sekarang, yang disebut ambtenaar adalah pegawai negeri. Jadi, Toean Moerdiyono Danoesastro sudah
tergolong sebagai priyayi kala itu.
Setelah
menjadi milik Moerdiyono Danoesastro, pada tahun 1970 fungsi bangunan rumah
tersebut dirubah menjadi homestay. Homestay ini sampai sekarang masih
mempertahankan bentuk bangunan aslinya yang bergaya Indis di mana antara
tradisional khas Jawa yang dibalut dengan gaya khas Eropa. Rumah yang menghadap
ke arah barat dan selatan ini memiliki dua lantai dengan balkonnya yang khas.
Keunikan yang lainnya adalah memiliki atap bangunan yang sangat curam. Awalnya
atap tersebut terbuat dari sirap, akan tetapi sekitar tahun 2005 sirap tersebut
diganti dengan genteng dengan alasan untuk mempermudah perawatan dan
pemeliharaan.
Bila
Anda sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta, sempatkanlah mengunjungi bangunan
bergaya Indis ini. Atau, bisa juga Anda menginap di homestay tersebut sekalian menikmati suasana tempo doeloe. Karena bangunan Indraloka Family
Homestay ini telah menjadi Bangunan Warisan Budaya (BWB) dengan nomor
798/KEP/2009. *** [010417]
Foto
: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo
Kepustakaan:
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/24/selayang-pandang-homestay-indraloka/
https://ugm.ac.id/id/berita/3378-umar.kayam.sastrawan.peduli.%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Cwong.cilik%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2
Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoKamis, Mei 11, 2017Eye Hospital of Dr. Yap, Jogja Heritage, kekunaan, Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta, Sejarah Rumah Sakit Mata Dr. Yap
Tidak ada komentar

Jalan
kaki dari Gedung PSKK UGM menuju Stasiun Yogyakarta usai menghadiri undangan
diskusi dari Medang Heritage Sociery
(MHS), cukup lumayan jauh. Jaraknya mendekati 4 kilometer, namun rasa capek di
kaki serasa menguap manakala menyaksikan bangunan-bangunan lawas yang membentang sepanjang perjalanan. Salah satu bangunan lawas yang masih bisa dilihat adalah
Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Rumah sakit ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 5
Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Lokasi rumah sakit ini berada di sebelah utara BRI Cabang
Cik Di Tiro, dan tidak begitu jauh dari Rumah Sakit Panti Rapih.
Keberadaan
rumah sakit ini tidak lepas dari prakarsa dan usaha dari dr. Yap Hong Tjoen.
Dr. Yap adalah anak muda Tionghoa kelahiran Yogyakarta 30 Maret 1885, yang
berpikiran besar jauh sebelum adanya Indonesia merdeka atau beberapa tahun
sebelum ikrar sumpah pemuda disuarakan.
Era
Hindia Belanda, selain orang Belanda banyak orang yang tidak bisa bersekolah.
Yap Hong Tjoen agak beruntung dibandingkan dengan anak seusianya kala itu,
karena berkesempatan mengenyam pendidikan sampai ke Negeri Belanda. Yap Hong
Tjoeng berangkat ke Leiden untuk melanjutkan studi dengan bidang spesialisasi mata.
Yap Hong Tjoen menjadi mahasiswa Tionghoa dari Hindia Belanda pertama yang
mempertahankan tesisnya di Leiden pada 19 Januari 1919.
Selama
belajar di Negeri Belanda, Yap Hong Tjoen juga gemar melakukan kegiatan di
dalam berbagai organisasi, seperti Chung
Hwa Hui (CHH), Indonesisch Verbond
van Studeerenden (IVS) atau Perserikatan Pelajar Indonesia (PPI). Dari
situlah kemudian timbul hasrat untuk mengamalkan keahlian dan kepandaiannya
kepada masyarakat di Hindia Belanda.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Negeri Belanda, dr. Yap Hoeng Tjoen berusaha merealisasikan cita-citanya setibanya di Hindia Belanda. Dilandasi keinginan menolong masyarakat Hindia Belanda yang menderita penyakit mata dan kebutaan, dr. Yap Hong Tjoen bersama beberapa warga keturunan Tionghoa dan keturunan Belanda mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Centrale Vereeniging tot bevordering der Oogheelkunde in Nederlandsch-Indie (CVO). Perkumpulan yang berkedudukan di Batavia ini berdiri pada tanggal 24 September 1920, dan dicatatkan di Notaris Mr. A.H. van Ophuijsen serta diumumkan kepada khalayak melalui media massa Javasche Courant No. 96 tertanggal 30 November 1920.
Pendirian
CVO, memiliki tujuan untuk menolong penderita penyakit mata, memberantas
kebutaan, dan memperbaiki nasib penyandang tunanetra, serta memajukan ilmu
penyakit mata. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan berbagai usaha,
di antaranya adalah mendirikan rumah sakit dan klinik untuk penderita penyakit
mata, dan memberi bantuan kepada lembaga lain yang bermaksud memberikan sarana
tersebut.
Berdasarkan
kuasa yang diterima oleh CVO, dr. Yap Hong Tjoe membangun sebuah rumah sakit di
atas lahan seluas 2.995 m² di Yogyakarta di Jalan Cik Ditiro (dulu bernama Yap Boulevard). Untuk mewujudkan rumah
sakit ini, Yap Hong Tjoe berusaha mencari dana untuk pembangunannya. Dana yang
diperoleh antara lain dari Pemerintah Hindia Belanda, Kesultanan Yogyakarta,
perusahaan perkebunan dan para dermawan.
Setelah
dana terkumpul, CVO mempercayakan desain bangunannya kepada Eduard Cuypers,
seorang arsitek terkenal berkebangsaan Belanda. Cuypers bekerja dari jarak jauh
di Amsterdam. Fermont dan kolega-kolega lain merealisasikan gagasan Cuypers
dari kantor biro arsitek ternama di Batavia, NV Architecten-Ingenieursbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers
te Amsterdam. Pada tahun tersebut, nama Hulswit sudah tidak dicantumkan
lagi pada nama biro arsitek tersebut karena Hulswit sudah meninggal pada tahun
1921.
Menurut
prasasti yang berada pada dinding teras bawah sisi barat yang berbentuk
persegi, peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit mata dilakukan oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono VIII pada tanggal 21 November 1922 (De Eerste Steen Geledg Door Z.H Hamengkoe Boewono VIII Op Den 21 Sten
Nov 1922).
Pada tanggal 29 Mei 1923 rumah sakit mata ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock, yang mendapat kuasa dari Ratu Belanda. Rumah sakit mata tersebut kemudian diberi nama Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders, yang artinya Rumah Sakit Mata Putri Juliana untuk Penderita Penyakit Mata. Selain itu, rumah sakit mata ini juga sering disebut Rumah Sakit CVO, dan oleh CVO sendiri dr. Yap Hong Tjoen diangkat sebagai direktur.
Untuk
melanjutkan cita-citanya dan melaksanakan tujuan pendirian CVO (pasal 2 stauten v/d CVO, tentang tujuan
pada butir (d), yaitu memperbaiki penyandang tunanetra), maka pada tanggal 12
September 1926, dr. Yap Hong Tjoen mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Stichting Voerstenlandsch Blinden Instituut.
Lembaga ini bertujuan memberikan keterampilan kepada penyandang tunanetra yang
berasal dari berbagai pelosok pedesaan.
Pada tahun
1927 Voerstenlandsch Blinden Instituut
mendirikan panti perawatan dan pendidikan keterampilan bagi penyandang
tunanetra. Panti ini kemudian diberi nama Balai Mardi Wuto. Di Balai Mardi
Wuto, para penyandang tunanetra dididik dan diberi keterampilan supaya dapat
mandiri dan menjadi lebih baik kesejahteraannya.
Sampai
sebelum pendudukan Jepang di Indonesia, Prinses
Juliana Gasthuis voor Ooglijders dan Balai Mardi Wuto mengalami
perkembangan yang cukup baik. Banyak penderita penyakit mata dapat tertolong
sedangkan yang mengalami kebutaan banyak ditampung dan diberi pendidikan dan
keterampilan guna membekali hidupnya.
Ketika
Jepang menduduki Yogyakarta pada tahun 1942, Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders berganti nama menjadi
Rumah Sakit Mata Dr. Yap untuk menghilangkan yang ada hubungannya dengan
pemerintahan penjajah Belanda. Namun demikian, Rumah Sakit Mata Dr. Yap tetap
diusik oleh bala tentara pendudukan Jepang bahkan dr. Yap Hong Tjoen ditangkap
dan ditawan. Sejak saat itu hingga sekarang nama Rumah Sakit Mata Dr. Yap tidak
pernah mengalami perubahan.
Pada tahun
1948, dr. Yap Kie Tiong putra dr. Yap Hong Tjoen kembali ke Indonesia setelah
menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Melalui Akta Notaris No. 53 tanggal 17
Juni 1949 dihadapan Notaris J. Hofstade di Semarang, dr. Yap Hong Tjoen
menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada putranya dr. Yap Kie Tiong. Selama
kepemimpinan dr. Yap Kie Tiong sampai beliau wafat tanggal 9 Januari 1969 tidak
ada perubahan struktur dewan pengurus. Sebelum meninggal dr. Yap Kie Tiong
sempat menulis sepucuk surat wasiat berkaitan dengan kelangsungan Rumah Sakit
Mata Dr. Yap yang ditujukan kepada Kanjeng Gusti Paku Alam VIII, Soemito Kolopaking,
Soemarman, dan dua orang anggota yang tidak disebutkan namanya. Isi wasiat
tersebut antara lain permintaan mengambil alih Rumah Sakit Mata Dr. Yap guna
kepentingan masyarakat.
Setelah
dr. Yap Kie Tiong tiada, Rumah Sakit Mata Dr. Yap sempat mengalami kekosongan
pimpinan sehingga mempengaruhi kelangsungan kegiatan rumah sakit. Kemudian
dibentuklah yayasan penyantun Rumah Sakit Mata Dr. Yap Prawirohusodo sebagai
pengelola Rumah Sakit Mata Dr. Yap.
Pada
tanggal 1 Agustus 2002 Yayasan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Prawirohusodo berubah
menjadi Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo sampai sekarang. Yayasan inilah yang
mengkoordinir Rumah Sakit Mata Dr. Yap dan Badan Usaha Sosial Mardi Wuto. *** [010417]
Foto:
Rilya Bagus Ariesta Nico Prasetyo
Kepustakaan:
http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-02-04/republika_2011-02-04_024.pdf
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/01/29/lintasan-sejarah-rumah-sakit-mata-dr-yap-yogyakarta/
http://www.norbruis.eu/opdrachten/onderzoek-penelitian/cuypers-hulswit/
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/40027
https://repository.usd.ac.id/2650/2/022214134_Full.pdf
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/2627-dr-yap-hong-tjoen-pendiri-rs-mata-dr-yap-di-yogyakarta
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoSenin, April 17, 2017Jogja Heritage, kekunaan, Panti Rapih Hospital, Rumah Sakit di Jogja, Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, Sejarah Rumah Sakit Panti Rapih
2 komentar

Tanggal
1 April 2017, saya mendapat undangan diskusi dari Medang Heritage Society (MHS) di Ruang Seminar Agus Dwiyanto,
Gedung Masrisingarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK)
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Usai diskusi, saya mencoba melakukan
jalan kaki dari PSKK menuju ke Stasiun Yogyakarta. Tujuannya, selain melemaskan
otot-otot di badan juga melihat-lihat bangunan lawas yang ada di Yogyakarta di antaranya adalah Rumah Sakit (RS) Panti
Rapih.
Rumah
sakit ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 30 Kelurahan Terban, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi
rumah sakit ini berada di tenggara bundaran UGM atau sebelah barat SPBU
Pertamina 44.552.12.
Berdasarkan
papan nama yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,
diketahui bahwa bangunan RS Panti Rapih merupakan bekas bangunan Onder de Bogen Hospitol. Berawal dari
pembentukan yayasan Onder de Bogen (Onder de Bogen Stichting) oleh pengurus
Gereja Yogyakarta, kemudian diteruskan untuk mendirikan sebuah rumah sakit
dengan meminta bantuan kepada Suster-suster Carolus Borromeus yang berpusat di
Maastricht Belanda.
Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nyonya C.T.M. Schmutzer van Rijckevorsel pada tanggal 14 September 1928. Nyonya C.T.M. Schmutzer van Rijckevorsel adalah istri Ir. Julius Robert Anton Marie Schmutzer, seorang administratur onderneming Gondang Lipoero Ganjuran Bantul, dan juga pernah menjadi murid sekolah perawat yang dikelola oleh Suster Carolus Borromeus di Belanda.
Pembangunan
rumah sakit ini dapat diselesaikan pada pertengahan Agustus 1929, dan pada
tanggal 24 Agustus 1929 Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, SJ berkenan
memberkati bangunan rumah sakit tersebut. Kemudian pada tanggal 14 September
1929 rumah sakit dibuka secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII
dengan nama Rumah Sakit Onder de Bogen.
Sesuai
namanya, bangunan rumah sakit ini banyak dihiasi dengan lengkungan-lengkungan (bogen). Lengkungan-lengkungan ini yang
menjadi kekhasan dari bangunan rumah sakit tersebut. Bangunan rumah sakit ini
dirancang oleh seorang arsitek bernama Ir. Frans Johan Louwrens Ghijsels dari Algemeen Ingenieur Architectenbureau
(AIA).
Para
suster melayani dan merawat orang sakit, meringankan penderitaan sesama sesuai
dengan ajaran Injil tanpa memandang agama dan bangsa. Sedikit demi sedikit
penderita datang dan semakin lama semakin bertambah dan meningkat jumlahnya.
Pasiennya sebagian besar adalah para pejabat Belanda dan kerabat Kraton. Sultan
Hamengku Buwono VIII menjelang wafatnya juga pernah dirawat di rumah sakit ini.
Pada
tahun 1942 Jepang datang ke bumi Nusantara untuk mendudukinya, tak terkecuali
Yogyakarta. Pada masa pendudukan inilah, RS Onder de Bogen tidak luput dari
penguasaan Jepang. Para Suster Belanda diinternir dan dimasukkan ke kamp
tahanan Jepang. Akibatnya, pengelolaan rumah sakit menjadi kacau balau.
Pemerintah Jepang menghendaki agar segala sesuatu yang berbau Belanda untuk dihilangkan,
termasuk salah satunya penggantian nama rumah sakit ini. Akhirnya, rumah sakit
ini diberi nama baru “Rumah Sakit Panti Rapih”, yang berarti Rumah Penyembuhan
oleh Mgr. Albertus Soegijopranoto, SJ (Uskup pada Keuskupan Semarang).
Setelah
Indonesia merdeka, para pejuang kemerdekaan semasa Revolusi Nasional dirawat di
rumah sakit ini termasuk Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia
Jenderal Sudirman. Pada waktu dirawat di rumah sakit ini, beliau pernah
menuliskan sebuah sajak yang berjudul “Rumah nan Bahagia”, yang hingga kini masih
tersimpan dengan baik.
Kini,
RS Panti Rapih berkembang menjadi rumah sakit swasta Katolik yang terkemuka di
Kota Yogyakarta, dengan pelayanan dan pengelolaan yang modern. *** [150417]
SGPC Bu Wiryo 1959 Yogyakarta
Budiarto Eko KusumoRabu, Desember 07, 2016Jogja Heritage, kekunaan, Pecel Rice of Bu Wiryo, SGPC Bu Wiryo 1959 Yogyakarta, Warung Makan Jogja Tempo Doeloe, Wisata Kuliner Jogja
Tidak ada komentar

Pagi
itu diiringi udara segar, kami berangkat dari Wonosalam Kreco menuju Kampus UGM
dengan menggunakan mobil sedan Hyundai. Karena masih jauh dari jam undangan
lokakarya How to Communicate Science?
Using Blood-Based Biomarkers in Health Research di Gedung Pasca Sarjana
Fakultas Kedokteran UGM, laju mobil yang saya sopiri berjalan dengan santai
sambil menikmati suasana jalan.
Sebetulnya
saya kurang menguasai jalan tersebut, tapi karena yang saya sopiri adalah
seorang post doctoral luar negeri
yang kebetulan S1 nya dari UGM maka perjalanan tersebut menjadi mudah. Maklum
tujuan dari lokasi yang ada di undangan merupakan wilayah semasa kuliahnya.
Sebelum memasuki Kampus UGM, saya diajak sarapan di sebuah warung makan Jogja Tempo Doeloe yang bernama SGPC Bu
Wiryo. Warung tersebut terletak di Jalan Agro CT VIII A-10 Klebengan, Kelurahan
Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lokasi warung ini tepat berada di seberang Fakultas Kedokteran Hewan UGM.
Sambil pesan makanan, saya pun berusaha menanyakan mengenai perjalanan warung ini. Warung ini dirintis oleh Bu Wiryo dengan berjualan nasi di halaman Fakultas Teknologi Pertanian UGM pada tahun 1959. Menu yang digandrungi para mahasiswa kala itu adalah nasi pecel, atau yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sego pecel. Dari kata sego pecel inilah kemudian disingkat menjadi SGPC. Menu lainnya yang tersaji di warung ini selain nasi pecel adalah sop dengan lauk tahu, tempe, dan telur ceplok. Ada kesan beda dengan pecel-pecel lainnya. Umumnya bumbu pecel hanya disajikan dengan rasa pedas. Namun kita akan merasakan perpaduan antara pedas dan manis pada bumbu kacang di SGPC Bu Wiryo ini. Sayur sop SGPC lebih khas dengan tambahan berupa soun.
Kemudian
pada tahun 1994, warung Bu Wiryo pun pindah di tempat yang sekarang. Lokasinya
yang relative permanen ini, akhirnya berkembang terus. Tak hanya para mahasiswa
tapi khalayak pun juga mulai menyantap menu makanan yang ada di warung
tersebut. Mulai buka dari jam 06.00 sampai pukul 21.30, pengunjung akan dihibur
oleh Pecel 59 SGPC Accoustic Band Plus.
Menu
disediakan sesuai selera. Beberapa diantaranya, seperti SDSB (sop daging sayur
bayem), sop tanpa kawat (sop tanpa
soun), sop bubrah (sop yang diberi
bumbu kacang pecel), sop tanpa truk
(sop tanpa kol atau kubis), sop pegatan
(sop dan nasi dipisah), pecel kramas
(pecel diberi kuah sop), pecel pancasila
(pecel dengan telur puyuh 5 butir), pecel
diuwel-uwel (pecel dibungkus), dan yang agak baru SBY (sop bayem). Selain itu,
pengunjung juga bisa mencicipi soto maupun garangasem.
Untuk
minuman, julukan semacam itu juga berlaku. Sebut saja teh mrengut (teh kental), tirto
seto (air putih), teh kemul (teh
hangat), dan sengkuni (teh dicampur
jeruk). *** [231116]